ABSTRACT
The destruction of
Keywords : deterrence, nuclear strategy, strategic studies
Kemunculan senjata nuklir pasca Perang Dunia II menjadi titik penting dalam perkembangan ilmu strategi. Kehancuran total yang dialami Jepang setelah pengeboman oleh Amerika Serikat dan keberhasilan Uni Soviet mengembangkan senjata nuklir di tahun 1949 telah memunculkan sebuah pertanyaan krusial yang akan coba dijawab dalam tulisan ini. Pertanyaan yang kemudian muncul adalah apakah konsep deterrence yang dikembangkan oleh AS dan Soviet pasca PD II merupakan sebuah strategi? Pertanyaan ini menjadi penting untuk dikaji dalam studi strategis karena menunjukkan adanya sebuah perubahan ataupun perkembangan dalam studi ini yang kemudian mempengaruhi perubahan-perubahan selanjutnya.
Untuk menjawab pertanyaan tersebut, tulisan ini dibagi menjadi beberapa bagian. Bagian pertama mencoba menjelaskan apa sebenarnya strategi itu. Bagian kedua mencoba melihat bagaimana perkembangan studi strategis pasca kemunculan senjata nuklir. Pada bagian selanjutnya, penulis mencoba menelaah prinsip dasar strategi yang diterapkan dalam konsep deterrence. Di bagian terakhir, penulis mencoba memberikan pandangan mengenai ada tidaknya sebuah konsep strategi nuklir yang dalam hal ini menitikberatkan pada konsep deterrence.
I. Apa itu Strategi ?
Sebelum melangkah lebih jauh dengan mendefinisikan strategi menurut beberapa ahli, satu hal yang perlu diingat adalah tujuan dari bagian ini adalah menjelaskan pengertian dasar strategi sehingga nantinya akan membawa kepada pengertian mengenai strategi nuklir. Strategi nuklir sendiri dianggap muncul pasca munculnya senjata nuklir, yaitu pasca Perang Dunia II. Oleh karenanya, pengertian strategi yang akan diambil dimulai dari strategi klasik sampai pada strategi era Perang Dingin.
Strategi berasal dari bahasa Latin strategos, yang artinya adalah jenderal yang terpilih[1]. Namun dalam sumber lain, strategi juga diambil dari bahasa Latin strategia yang artinya adalah seni para jenderal (generalship)[2]. Kedua pengertian diatas diambil secara epistemologis dan merupakan sebuah terjemahan dari bahasa lain. Dari kedua pengertian diatas, strategi bisa kita kaitkan dengan para jenderal, dan jenderal amat dekat dengan perang. Itulah sebabnya mengapa para teoretisi mengenai strategi di era strategi klasik seperti Sun Tzu, Carl von Clausewitz, Liddell Hart, dan Henri de Jomini serta Macchiavelli selalu menggunakan kata ”War” sebagai bagian integral dari judul buku mereka.
Sementara itu, strategi juga bisa kita artikan dari beberapa pandangan para pengamat yang mencoba menelaah mengenai strategi. Clausewitz misalnya menganggap bahwa strategi adalah ”the use of engagements for the object of war”. Liddell Hart memberikan definisi lain mengenai strategi yaitu seni mendistribusikan dan menggunakan cara-cara militer untuk mencapai kepentingan. Von Moltke mengartikan strategi sebagai sebuah upaya adaptasi praktis oleh seorang jenderal terhadap pilihan-pilihan dan cara-cara yang dipunyainya untuk pencapaian tujuan dalam peperangan [3].
Ketiga pengertian yang telah disebutkan sebelumnya adalah pengertian strategi di era klasik, yaitu sebuah era ketika perang dan strategi masih amat dekat posisinya. Strategi selalu diartikan sebagai sebuah upaya untuk mencapai tujuan dalam peperangan. Yang perlu dicatat dalam hal ini adalah Clausewitz telah memberikan sebuah dasar mengenai strategi dan perang dengan mengatakan bahwa perang hanyalah sebuah alat pencapaian kepentingan[4]. Dengan menyatakan bahwa perang tak lebih dari perpanjangan politik dan kebijakan untuk memperoleh kepentingan melalui cara lain, maka Clausewitz telah mengubah dasar berpikir yang ada sebelumnya seperti di era Sun Tzu yang menganggap bahwa perang adalah merupakan kepentingan terbesar dari sebuah negara[5].
Terdapat perbedaan yang cukup signifikan antara pengertian strategi era klasik dengan strategi-strategi di era selanjutnya. Michael Porter menganggap bahwa elemen penting strategi adalah ketika kita memilih untuk melakukan hal yang berbeda dengan rival kita. D’Aveni memberikan pandangan bahwa strategi tidak saja menciptakan posisi yang lebih menguntungkan bagi kita namun juga melemahkan posisi lawan[6]. Robert Greene dalam bukunya yang terkenal, 33 Strategi Perang, memberikan sebuah pernyataan menarik. Ia menyatakan bahwa yang terpenting dalam strategi bukanlah untuk memenangkan pertempuran melainkan untuk memberikan kita lebih banyak pilihan bertindak daripada lawan ataupun saingan kita[7].
Dari beberapa pengertian lanjutan yang telah diberikan, nampak sebuah perubahan pola pikir dalam memahami strategi. Apabila di era sebelumnya strategi lebih diarahkan kepada sebuah upaya pencapaian kepentingan dalam peperangan, maka di era selanjutnya strategi lebih merupakan sebuah pola berpikir untuk mendapatkan keuntungan maupun kepentingan. Hal ini akan sangat berpengaruh terutama dalam memahami strategi yang, menurut beberapa pihak, dikembangkan di era nuklir.
II. Konsep Dasar Strategi di Era Nuklir
Dalam era persaingan nuklir, terdapat beberapa konsep dasar strategi yang mengalami perubahan bila kita bandingkan dengan strategi di era sebelumnya. Dari bab sebelumnya, kita bisa mengambil beberapa konsep dasar strategi yang menjadi pedoman kita dalam memahami strategi di era nuklir. Salah satu doktrin utama strategi, mengutip Clausewitz dan Liddell Hart, adalah kaitan erat antara strategi dan perang. Strategi dgunakan untuk mencapai tujuan dalam peperangan. Di era kontestasi nuklir antara Amerika Serikat dan Uni Soviet periode 1949-1989, tidak ada perang langsung antar keduanya. Dengan kata lain, tidak ada perang nuklir yang terjadi. Satu-satunya insiden yang cukup dekat dan hampir saja menciptakan perang nuklir adalah Cuban Missile Crisis tahun 1962. Selain itu, kedua kekuatan nuklir ini tidak pernah saling berperang dan dengan demikian menyulitkan kita untuk menganalisis konsep strategi sebagai pemenuhan tujuan dalam peperangan.
Salah satu konsep lain yang mungkin bisa dijadikan patokan dalam menelaah strategi era nuklir adalah konsep Michael Porter yang telah disebutkan sebelumnya. Porter berpendapat bahwa strategi berarti kita melakukan tindakan ataupun aktivitas yang berbeda dengan lawan kita ataupun saingan kita. Nampaknya Porter mendasarkan asumsinya pada kondisi persaingan yang apabila kita melakukan hal yang sama dengan pesaing kita maka kita akan mendapatkan hasil yang sama dan kita tidak akan bisa mengungguli saingan kita tersebut.
Apabila prinsip ini kita terapkan dalam skema persaingan kepemilikan nuklir, maka konsep ini memiliki 2 sisi yang berbeda. Sisi pertama, konsep ini jelas masih relevan. Ini dikarenakan kenyataan bahwa ketika AS mengembangkan nuklirnya di tahun 1940an, maka tahun 1949 Uni Soviet kemudian memunculkan nuklir yang lebih kuat. Demi memenangkan persaingan tersebut, AS lantas mencoba menciptakan bom hidrogen, yang jauh lebih kuat daripada bom atom yang meluluh-lantakkan Nagasaki dan Hiroshima dan kemudian mendirikan NATO, menciptakan negara Jerman Barat yang demokratis, dan tetap menempatkan pasukan di Jepang untuk memperkuat posisi mereka[8]. Ketika salah satu pihak menerapkan sebuah kebijakan, maka pihak lain akan mencari kebijakan yang lebih efektif dari pihak lawannya.
Namun, disisi lain, fakta menunjukkan bahwa salah satu konsep ”strategi”[9] yang dianggap amat erat kaitannya dengan nuklir adalah deterrence. Konsep deterrence yang cukup dikenal adalah tidak adanya pihak yang mampu menahan serangan nuklir dan oleh karenanya tidak akan ada pihak yang mencoba menyerang pihak lain dengan nuklir. Namun untuk menciptakan kondisi ini, jelas kedua pihak perlu memiliki kekuatan yang kurang-lebih sama, ataupun masing-masing pihak memiliki kekuatan nuklir. Dalam kasus ini bukan inovasi seperti yang diharapkan Porter yang akan terjadi melainkan perlombaan senjata nuklir dengan kondisi masing-masing pihak berupaya menyamai kekuatan pihak lain, bukan melebihinya.
Konsep lain yang bisa kita elaborasi dengan keadaan nulir adalah pendapat D’Aveni yaitu mengenai konsep strategi sebagai alat memperkuat diri dan juga memperlemah lawan. Dalam era nuklir, strategi bisa jadi akan dipakai untuk memperkuat posisi tawar suatu pihak (dalam hal ini negara) dalam hubungannya dengan negara lain. Namun, dari sejarahnya, nuklir tidak bisa dipakai sebagai alat memperoleh kepentingan. Ini terkait konsep deterrence yang telah dijelaskan sekilas diatas, dan akan dijelaskan dengan lebih jelas pada bab selanjutnya. Intinya, nuklir kemudian berkembang menjadi ”unusable weapon” karena penggunaan secara harfiah akan menyebabkan kehancuran total bagi musuh kita dan bagi diri kita sendiri.
Konsep terakhir yang coba diketengahkan disini adalah strategi sebagai sarana bagi kita untuk memperoleh lebih banyak pilihan dibandingkan dengan musuh maupun pesaing kita. Di era nuklir, cukup sulit melihat hal ini terjadi. Ini disebabkan nuklir justru mengurangi opsi-opsi yang dimiliki oleh para pengambil keputusan. Dalam kondisi konvensional (tanpa nuklir), maka pengambil keputusan dalam suatu negara bisa memilih berbagai kebijakan demi mencapai kepentingannya. Namun, bila dalam kondisi persaingan nuklir, maka pilihan yang bisa diambil bukanlah bertambah melainkan berkurang. Sebagai contoh, ketika Amerika Serikat berhasil menciptakan bom atom dan menggunakannya di Jepang, maka satu-satunya pilihan bagi Uni Soviet saat itu adalah mereka harus memiliki senjata nuklir pula agar mereka tidak rentan diserang oleh AS. Kondisi yang sama terjadi ketika Uni Soviet berhasil mengembangkan nuklir tahun 1949. Amerika Serikat langsung menyadari bahwa opsi-opsi untuk menyerang Soviet telah pupus, dan sekarang mereka harus menciptakan senjata yang bisa jadi jauh lebih kuat daripada nuklir Soviet.
Perbedaan ini amat terasa bila dibandingkan dengan keadaan perang konvensional. Perang konvensional yang terjadi pada PD I dan PD II memberikan banyak opsi bagi negara, apakah itu serangan darat, udara, laut, maupun lewat serangan kombinasi. Namun disisi lain, konsep Greene ini bisa jadi masih relevan bila kita lihat potensi nuklir sebagai penguat posisi tawar sebuah negara. Kita bisa lihat Iran yang begitu ingin mengembangkan nuklir mandiri. Walaupun begitu, anggapan bahwa nuklir memberikan posisi tawar lebih bagi negara ini masih bisa diperdebatkan.
Setelah melihat dan menelaah beberapa pandnagan diatas, maka bisa jadi kita akan tiba pada kesimpulan bahwa strategi nuklir tidaklah ada karena beberapa konsep dasar strategi telah dipatahkan dengan beberapa fakta dan asumsi yang ada. Namun terlalu dini untuk menyimpulkan hal itu. Ini dikarenakan kita masih belum membahas mengenai konsep ”strategi nuklir” yang selama ini dianut dan dipercayai oleh AS dan Uni Soviet. Pada bab selanjutnya penulis akan mencoba memaparkan salah satu dari strategi nuklir tersebut.
III. Telaah Kritis Strategi Era Nuklir : Studi Kasus Konsep Deterrence
Untuk memberikan gambaran lain mengenai sebuah konsep strategi nuklir, maka kita perlu menelaah ”strategi” yang dianggap merupakan strategi nuklir oleh beberapa pemikir dan terutama oleh pengambil keputusan di Amerika Serikat dan Uni Soviet. Salah satu strategi yang cukup dikenal oleh masyarakat awam adalah deterrence. Jan Lodal mengungkapkan bahwa sejak awal konsep deterrence ini dimunculkan karena begitu tingginya tingkat kekuatan dari senjata nuklir yang mengakibatkan hampir tidak ada yang mampu menahan daya hancurnya[10]. Walaupun konsep mengenai deterrence ini sebenarnya telah ada sebelum kemunculan senjata nuklir, namun keberadaan nuklir menjadi salah satu dasar pemikiran yang membuat AS dan Uni Soviet menerapkan konsep deterrence ini. Konsep ini, dalam hal senjata nuklir, didasarkan pada kemampuan nuklir untuk menghancurkan peradaban salah satu pihak yang menyerang terlebih dahulu bila pihak yang diserang melakukan serangan balasan[11]. Oleh karenanya, senjata nuklir ini amat berguna justru dalam kondisi tidak terpakai.
Yang perlu kita kritisi dari konsep deterrence ini adalah apakah deterrence ini, kondisi ketika pihak-pihak yang terlibat dalam konflik saling bersaing meningkatkan kemampuan nuklirnya namun tidak untuk digunakan, adalah sebuah strategi?
Leo Tolstoy dalam bukunya ”War and Peace” bahkan melakukan sebuah dekonstruksi terhadap konsep strategi dan perang konvensional[12]. Ia beranggapan bahwa dalam peperangan tidak ada yang pasti dan setiap upaya untuk menggeneralisasi keberhasilan seorang jenderal dalam sebuah konsep strategi adalah ilusi belaka. Dalam beberapa perang, seperti PD II, kemenangan datang karena kebetulan belaka, dan karena kemampuan prajurit di lapangan melakukan taktik yang tepat, bukan karena strategi yang benar dari para pemimpinnya.
Salah satu kritik lain yang bisa diberikan adalah bahwa strategi deterrence nuklir ini seperti permainan catur, dimana secara tiba-tiba musuh memiliki bidak catur yang amat kuat yang tidak diikat oleh peraturan permainan. Kepemilikan bidak catur super itu sama sekali tidak mempengaruhi permainan dan tidak memberikan keuntungan apapun, karena sifatnya yang ”diluar” aturan dan permainan itu tadi. Akhirnya, setiap pihak berusaha menciptakan bidak super itu hanya karena lawan juga memilikinya[13].
Hans Morgenthau memberikan beberapa kritik penting yang bisa dijadikan masukan bagi kita untuk menelaah strategi deterrence ini. Salah satu yang penting adalah bagaimana sebuah strategi yang meniadakan pencapaian kepentingan bisa dikatakan strategi?[14] AS dan Soviet dalam beberapa kasus jelas-jelas menyatakan tidak akan menggunakan senjata nuklirnya. Lantas apa kegunaan dari senjata nuklir itu sendiri? Dan ketika senjata itu tidak bisa digunakan (engagements dalam istilah Clausewitz), maka dimana letak kekuatan strategi itu?
Bila kita mengingat bahwa salah satu konsep utama strategi yang hampir senada dalam semua ahli adalah strategi ditujukan untuk pencapaian kepentingan. Selama ini, pencapaian kepentingan selalu diselaraskan dengan kemenangan maupun posisi tawar yang lebih tinggi ataupun juga kemampuan untuk memilih lebih banyak daripada lawan. Bila kita berpatokan pada konsep tersebut, akan sangat mudah bagi kita untuk menyimpulkan bahwa konsep deterrence sebagai strategi yang paling mewakili era nuklir (terutama era Perang Dingin) adalah bukan sebuah strategi seperti yang digambarkan para teoretisi.
Akan tetapi, tidak tertutup kemungkinan kitalah yang belum mencoba menelaah lebih jauh mengenai konsep strategi nuklir tersebut. Seperti yang diungkapkan Robert Greene, strategi tidaklah statis, strategi selalu dinamis dan menyesuaikan dengan keadaan lingkungan sekitarnya serta kebutuhan penyusun strateginya[15]. Bila kita memahami strategi sesuai dengan kondisi dan keadaan lingkungan saat strategi tersebut disusun, maka ada beberapa faktor yang kemudian bisa membuat deterrence yang dilakukan oleh AS dan Soviet digolongkan dalam klasifikasi strategi.
Pertama, dari segi strategi sebagai alat pencapaian tujuan dan kepentingan. Perlu diingat bahwa dalam era nuklir tahun 1949-1989, kondisi politik internasional saat itu didominasi oleh 2 kekuatan besar yaitu AS dan Uni Soviet. Keduanya jelas memiliki kepentingan masing-masing, namun keduanya sudah pasti memiliki kepentingan menjaga keamanan nasional masing-masing negara. Untuk itu, perlu kita pertimbangkan bahwa ketika Perang Dunia II berakhir, AS telah memiliki senjata nuklir. Dunia menyaksikan sendiri betapa dahsyatnya daya hancur dari senjata nuklir yang digunakan AS untuk meluluhlantakkan Jepang. Ada informasi menarik bahwa pembuatan senjata nuklir (atom saat itu) sebenarnya telah diberi peringatan oleh sang penemu, Robert Oppenheimer dan 2 orang petinggi pemerintah AS, Dean Acheson (Under Secretary of State) dan Bernard Baruch (Ambassador to UN Atomic Energy Commision). Mereka beranggapan bahwa walaupun penemuan ini revolusioner dan historis namun bila digunakan secara destruktif akan menghancurkan peradaban manusia[16].
Tidaklah mengherankan ketika kemudian Soviet merasa terancam dengan kepemilikan nuklir AS yang mampu menghancurkan peradaban ini. Satu-satunya jalan untuk menjaga keamanan dirinya adalah lewat konsep deterrence, yaitu dengan memiliki nuklir berkekuatan setara secara mandiri. Penulis kemudian juga menjadi lebih bisa memahami kebijakan AS untuk meningkatkan kemampuan nuklirnya setelah Soviet berhasil menciptakan senjata nuklir sendiri. Hal itu merupakan satu-satunya pilihan yang ada demi menjamin tercapainya kepentingan nasional AS dan Soviet saat itu, yaitu survival.
Yang kedua, strategi deterrence ini ternyata menunjukkan bahwa konsep melemahkan posisi lawan dan meningkatkan posisi tawar diri kita sendiri masih bisa digunakan. Perlu diingat bahwa di tengah ancaman serangan nuklir, opsi-opsi yang dimiliki suatu pihak ataupun negara menajdi terbatas dengan sendirinya dan, seperti argumen kelompok realis, dalam kondisi seperti itu maka survivalitas akan menjadi pertimbangan utama. Akan tetapi pemilihan survivalitas sebagai opsi utama bukan berarti meniadakan opsi lainnya. Terbukti, di awal persaingan dengan Soviet, AS sempat mengembangkan konsep Massive Retaliation (serangan balik yang masif) yang diyakini akan mampu menghancurkan Soviet sebelum mereka menyerang habis AS. Ini dikarenakan adanya posisi yang asimetris dalam kekuatan nuklir kedua pihak. Namun, seiring perkembangan kekuatan Soviet, doktrin-doktrin ini pun berubah menjadi ”Limited Retaliation” lalu ’Mutual Assured Destruction”.
Walaupun begitu, memang muncul banyak kritik seperti oleh Morgenthau yang mengkritik bahwa ada 4 paradoks yang muncul berkaitan dengan strategi nuklir (dalam hal ini deterrence). Pertama, komitmen untuk menggunakan senjata nuklir telah diganggu oleh ketakutan dalam penggunaan senjata tersebut. Kedua, adanya upaya pencarian sebuah strategi nuklir yang justru mencoba menghindari akibat dari perang nuklir. Ketiga, adanya upaya persaingan proliferasi nuklir yang diikuti upaya menghentikannya. Dan yang terakhir adalah upaya penciptaan aliansi tanpa penggunaan senjata nuklir[17]. Beberapa pihak juga menganggap bahwa konsep deterrence ternyata tidak ”men-deter” apapun selain dari senjata nuklir itu sendiri. Ini terbukti dari masih adanya perang antar kekuatan-kekuatan non-nuklir[18].
Beberapa strategi lain yang juga mewarnai era perlombaan senjata nuklir seperti “mutual asssured destruction”, “containment policy”, dan “counterforce-countervalue” didasarkan dan disandarkan pada konsep deterrence sebagai konsep utama dalam strategi nuklir AS dan Uni Soviet. Oleh karenanya, secara umum prinsip dari beberapa konsep yang disebutkan belakangan hampir sama dengan apa yang telah dijelaskan mengenai deterrence.
IV. Apakah Ada Strategi Nuklir : Telaah Konsep ”Deterrence”
Seperti yang telah dijelaskan pada bagian sebelumnya, ada pro-kontra mengenai kedudukan deterrence sebagai sebuah strategi nuklir. Beberapa pihak menyatakan bahwa strategi nuklir sebenarnya tidak ada dan hanya merupakan ilusi belaka[19]. Pihak lain seperti Morgenthau dan Brodie, walaupun memberikan kritik cukup tajam, tetap menganggap bahwa deterrence adalah sebuah strategi nuklir. Penulis beranggapan bahwa cukup sulit untuk memberikan ruang bagi deterrence dalam konsep strategi klasik. Strategi yang dipelopori oleh Sun Tzu dan Clausewitz ini masih melihat pentingnya pencapaian tujuan dalam peperangan, sementara dalam kasus nuklir ini, hampir tidak mungkin ada perang terbuka antar kekuatan nuklir.
Oleh karenanya, hal yang bisa dilakukan oleh penulis adalah mengklasifikasinya dalam konsep strategi yang berbeda dengan strategi klasik. Strategi nuklir, dalam hal ini deterrence, berbeda dengan strategi klasik dalam banyak hal. Pertama, tidak ada medan pertempuran yang mungkin menjadi ajang adu strategi antar pihak. Ini dikarenakan sifat nuklir yang begitu destruktif sehingga tidak memungkinkan adanya sebuah serangan awal yang sukses menghancurkan lawan ataupun kemenangan cepat seperti yang dipreskripsikan Sun Tzu.
Kedua, strategi nuklir tidak lagi hanya bertujuan melemahkan posisi lawan atau memperkuat posisi diri sendiri melainkan juga untuk bertahan hidup (survival) dan memenuhi kepentingan nasional masing-masing negara yaitu keselamatan warga dan keamanan nasional. Berbeda dengan konsep strategi klasik yang menginginkan kemenangan yang sempurna dengan menguasai lawan secara total dan berhasil menekan lawan agar melakukan sesuai yang kita inginkan, maka strategi nuklir tidak sampai memposisikan lawan dalam posisi yang kalah, namun yang terutama adalah mencapai kepentingan kita yaitu bertahan hidup dan keamanan nasional.
Beberapa orang mungkin menganggap perubahan yang terjadi ini sudah cukup untuk membuat strategi nuklir dianggap tidak ada. Namun, penulis beranggapan bahwa 2 konsep utama strategi yang dikemukakan Clausewitz dan Liddell Hart masih ada dalam konsep strategi nuklir, terutama deterrence ini. 2 konsep dasar tersebut adalah strategi sebagai alat pencapaian kepentingan dan strategi sebagai cara memperoleh opsi dalam penyusunan kebijakan.
V. Simpulan
Strategi nuklir, terutama deterrence, mungkin mulai dianggap usang pasca runtuhnya Uni Soviet dan hilangnya persaingan nuklir antar negara-negara di dunia. Namun, perlu diingat bahwa ada ungkapan :
Rational actors do not fight nuclear wars, but history is not
written about rational actors behaving in a rational manner[20]
Ungkapan diatas menunjukkan bahwa dalam sejarah tidak pernah ada sesuatu yang pasti. Walaupun negara-negara yang ada saat ini dianggap sebagai aktor rasional, namun itu tidak berarti mereka akan berhenti berperang dan akan berhenti berkonflik. Keadaan ini sama seperti yang diungkapkan Fred Iklé yang memprediksikan akan adanya era nuklir baru yang berpotensi sama berbahayanya dengan era Perang Dingin[21]. Negara-negara seperti Rusia akan beranggapan bahwa nuklir adalah cara yang paling efisien menjaga keamanan perbatasan negerinya, dikarenakan sebagai bekas Uni Soviet mereka memiliki banyak hulu ledak nuklir.
Di tengah banyaknya konflik bertendensi nuklir saat ini, seperti konflik AS-Iran dan permasalahan India-Pakistan serta Korea Utara, maka konsep strategi deterrence bisa kembali dilirik sebagai salah satu strategi yang berhasil meredam konflik nuklir di era Perang Dingin. Mengingat begitu berbahayanya nuklir sebagai sumber kehancuran peradaban, maka tidaklah mengherankan bila negara-negara di dunia kembali mengedepankan pola deterrence sebagai penahan terciptanya “Impossible War” yaitu perang nuklir.
[1] "strategy." Encyclopædia Britannica. 2009. Encyclopædia Britannica Online. 03 Jan. 2009 <http://www.britannica.com/EBchecked/topic/568259/strategy>.
[2] Fred Nickols, “Strategy : Definitions and Meanings”
[3] Joko Susanto, Kuliah Strategi dan Tata Kelola Strategis, 9 September 2008.
[4] Carl Von Clausewitz: On War, trans. J.J Graham (
[5] Sun Tzu: The Art of War, trans. Lionel Giles (
[6] Joko Susanto, loc.cit.
[7] Robert Greene, The 33 Strategies of War (
[9] Diberikan tanda kutip dikarenakan masih dipertanyakan apakah strategi nuklir memang ada. Mengenai hal ini akan dibahas lebih lanjut pada bagian selanjutnya.
[10]Jan M. Lodal, “Deterrence and Nuclear Strategy,” The MIT Press on behalf of American Academy of Arts & Sciences, Daedalus, Vol. 109, No. 4, U.S. Defense Policy in the 1980s (Fall, 1980), pp. 155-175, 3 January 2009
[11] Ibid.
[12] “Nuclear Strategy is an Oxymoron,” 3 January 2009 <http://www.spectacle.org/696/strat.html>.
[13] Ibid.
[14] Hans J. Morgenthau, “The Four Paradoxes of Nuclear Strategy,” American Political Science Association, The American Political Science Review, Vol. 58, No. 1 (Mar., 1964), pp. 23-35, 3 January 2009
[15] Greene, loc.cit.
[16] Bernard Brodie, “The Development of Nuclear Strategy,” The MIT Press, International Security, Vol. 2, No. 4 (Spring, 1978), pp. 65-83, 3 January 2009
[17] Morgenthau, loc.cit.
[18] “Nuclear Strategy is an Oxymoron”, loc.cit..
[19] Ibid.
[20] Anthony H. Cordesman, “
[21] Fred Charles Iklé, “The Second Coming of the Nuclear Age,” Council on Foreign Relations, Foreign Affairs, Vol. 75, No. 1 (Jan. - Feb., 1996), pp. 119-128, 3 January 2009
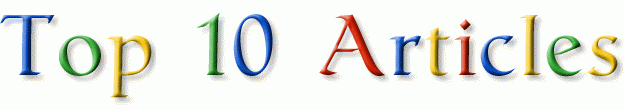
No comments:
Post a Comment